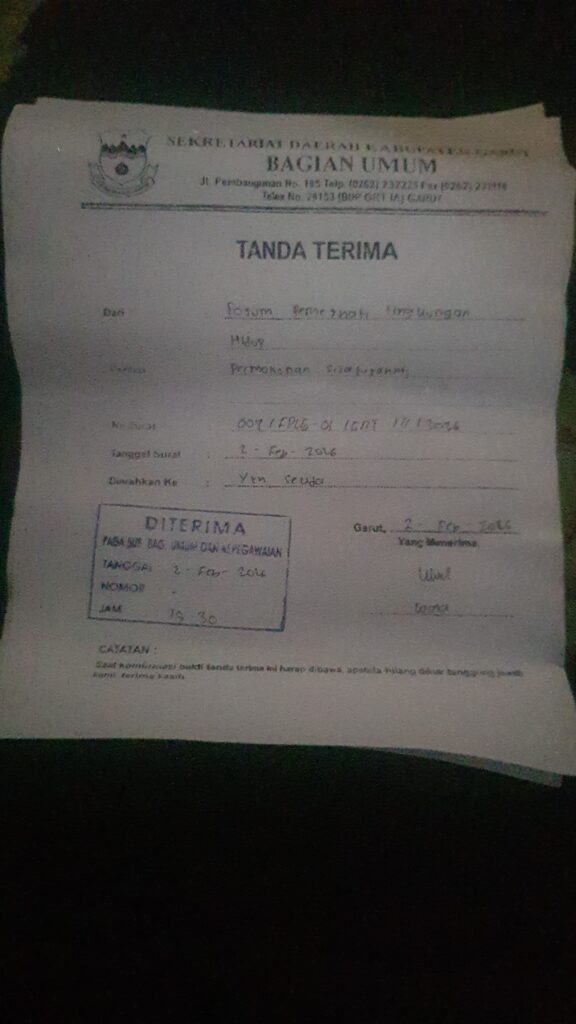![]()
Sumedang medialibas.com — Krisis iklim yang semakin nyata, banjir yang tak lagi musiman, kekeringan panjang, gagal panen, hingga krisis air bersih, bukanlah fenomena alam biasa. Semuanya merupakan alarm keras dari alam atas pengabaian manusia terutama pemangku kebijakan terhadap pentingnya perlindungan ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup.
Menurut Iwa Kartiwa, pemerhati lingkungan dari Perkumpulan Lingkungan Anak Bangsa (LIBAS), pemanfaatan kawasan saat ini kian mengabaikan aspek fundamental lingkungan: kajian daya dukung dan daya tampung kawasan. Padahal, dua aspek ini wajib menjadi dasar utama dalam setiap aktivitas pembangunan yang menyangkut ruang dan lingkungan.
“Jika daya dukung dan daya tampung tidak dijadikan rujukan utama, maka yang terjadi adalah kerusakan ekosistem, alih fungsi kawasan, dan pada akhirnya kehancuran keseimbangan kehidupan itu sendiri. Kita sedang menggali kubur kita sendiri,” tegas Iwa dalam wawancara khusus.Selasa,(03/06/2025).
Ia menyayangkan sikap pemerintah pusat maupun daerah yang dinilai tidak memiliki keberpihakan nyata terhadap lingkungan hidup. Proyek-proyek strategis nasional, kawasan industri baru, pembangunan perumahan skala besar, bahkan alih fungsi hutan menjadi area perkebunan dan tambang, terus dijalankan tanpa analisis mendalam mengenai kemampuan lingkungan untuk menanggungnya.
Membangkang Konstitusi, Mengabaikan Undang-Undang
Iwa mengingatkan bahwa pengabaian terhadap kajian daya dukung dan daya tampung tidak hanya mencederai moral ekologis, tapi juga melanggar hukum.
“Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) sudah sangat jelas menyebut bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup,” ujar Iwa mengutip Pasal 67 UU tersebut.
Lebih jauh, Pasal 37 UU PPLH juga menyatakan bahwa dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) wajib memuat kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Namun kenyataannya, banyak proyek berjalan dengan dokumen yang lemah, atau bahkan tanpa AMDAL yang sah.
Tak hanya itu, Pasal 69 ayat (1) huruf a UU PPLH menyebut bahwa perbuatan yang dilarang mencakup melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Sanksi pidana bagi pelanggar pun telah diatur tegas dalam Pasal 98 dan 99, termasuk pidana penjara hingga 10 tahun dan denda hingga Rp10 miliar.
“Kalau ini tidak disebut kejahatan lingkungan, lalu apa? Aparat penegak hukum pun harus lebih progresif. Jangan hanya menindak penambang ilegal, tapi membiarkan kejahatan sistematis yang merusak kawasan ekosistem penting,” katanya.
Krisis Iklim: Dampak Nyata dari Kerusakan Ekosistem
Iwa menambahkan bahwa kerusakan lingkungan bukanlah isu teknis, melainkan masalah hidup dan mati. Pemanasan global yang mendorong perubahan iklim ekstrem adalah hasil dari akumulasi kerusakan ekosistem—mulai dari hutan yang digunduli, rawa yang dikeringkan, hingga daerah resapan air yang diubah jadi beton.
“Banjir di kota-kota besar, kekeringan panjang di pedesaan, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga naiknya permukaan air laut semua ini akibat dari kerusakan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Ketika alam kehilangan kemampuan menampung aktivitas manusia, yang terjadi adalah bencana demi bencana,” jelas Iwa.
Ia mencontohkan tragedi banjir bandang di Sumatera Barat, longsor di Sumedang, serta kekeringan di Nusa Tenggara sebagai bukti bahwa kerusakan lingkungan telah melampaui ambang toleransi. “Jika tidak ada perubahan drastis dalam cara kita merencanakan pembangunan, maka kehancuran ekologis tinggal menunggu waktu,” tegasnya.
Menyerukan Tindakan Nyata dan Revolusi Ekologis
Iwa menyerukan agar pemerintah menghentikan kebijakan pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proyek yang memanfaatkan ruang kawasan, serta penguatan sistem audit lingkungan secara independen.
“Warga negara harus diberdayakan untuk turut mengawasi proyek-proyek pembangunan. Partisipasi publik dijamin dalam UU, terutama melalui mekanisme penyusunan AMDAL. Namun saat ini, seringkali masyarakat hanya dijadikan formalitas,” ujarnya.
Sebagai penutup, Iwa mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak tinggal diam. “Ini bukan soal hutan yang hilang atau sungai yang tercemar semata. Ini soal kelangsungan hidup manusia. Kita perlu revolusi ekologis bukan hanya dalam kebijakan, tapi dalam cara berpikir dan bertindak.”
Catatan Redaksi:
Berita ini ditulis berdasarkan hasil wawancara, penelusuran dokumen hukum, serta observasi berbagai kejadian bencana ekologis yang telah terjadi di Indonesia dalam satu dekade terakhir. Jika Anda memiliki informasi tambahan atau ingin menanggapi isu ini, silakan hubungi redaksi kami. (AA)