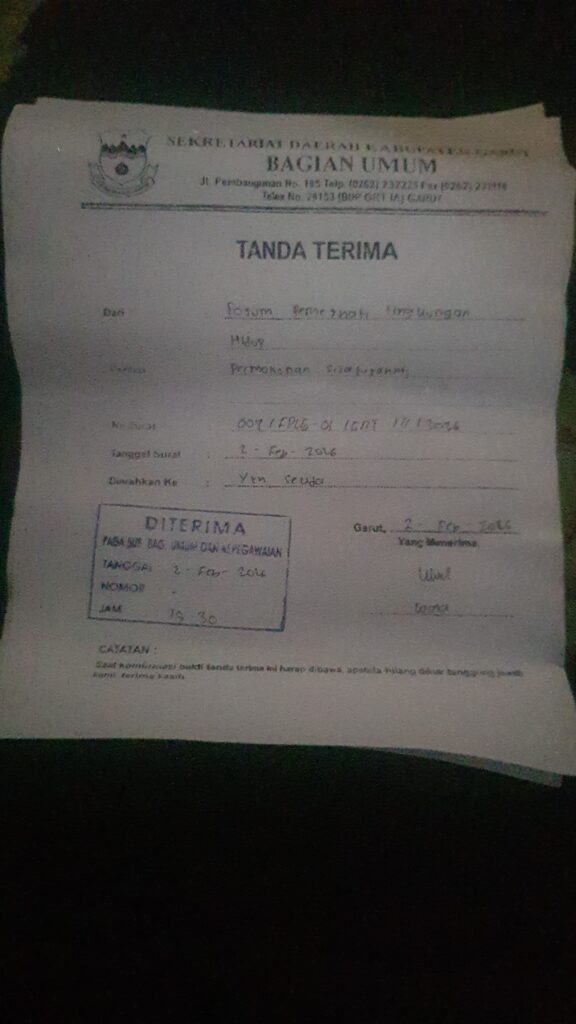![]()
Oleh: Ridwan Mustopa
(Dosen dan Praktisi Media)
Garut Opini, Medialibas.com – Demokrasi pada hakikatnya adalah ruang di mana setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat, baik melalui suara di bilik pemilu maupun aksi kolektif di jalanan. Dalam konteks inilah, unjuk rasa bukanlah ancaman, melainkan bagian integral dari praktik demokrasi. Akan tetapi, bagaimana publik memahami unjuk rasa tidak lepas dari peran media. Media bukan hanya “cermin” realitas, tetapi juga “pembentuk” realitas melalui bingkai pemberitaan yang dipilih.
Robert Entman dalam teori framing menegaskan bahwa media selalu memilih aspek tertentu dari peristiwa untuk ditonjolkan. Pertanyaannya, aspek apa yang lebih sering disorot media ketika memberitakan aksi unjuk rasa?
Apakah wajah kericuhan dan bentrokan, atau substansi aspirasi yang disuarakan masyarakat?
Pilihan framing ini akan sangat memengaruhi persepsi publik: apakah unjuk rasa dilihat sebagai kanal demokrasi yang sah, atau sebagai ancaman terhadap stabilitas negara.
Banjir Informasi dan Bias Konflik
Era digital menghadirkan tsunami informasi yang sulit dibendung. Media sosial, dengan algoritme yang lebih menyukai konten dramatis, sering kali menyoroti potongan-potongan video kerusuhan. Dampaknya, masyarakat cenderung terpapar narasi konflik yang menutupi akar permasalahan. Inilah yang saya sebut sebagai “bias konflik”.
Sayangnya, media arus utama terkadang terjebak dalam pola serupa. Pemberitaan lebih fokus pada jumlah korban, kerusakan fasilitas, atau aksi saling dorong dengan aparat. Padahal, di balik itu ada suara rakyat yang menuntut keadilan, kesejahteraan, atau kebijakan yang lebih berpihak. Jika media hanya menyoroti kekisruhan, demokrasi direduksi menjadi sekadar panggung kekacauan, bukan ruang dialog.
Media sebagai Jembatan Dialog
Peran media sejatinya bukan sekadar menyampaikan fakta, melainkan menghubungkan suara rakyat dengan pemerintah. Dengan pemberitaan yang proporsional, media bisa menghadirkan pemahaman utuh bahwa unjuk rasa adalah kanal demokrasi yang sah dan damai.
Lebih jauh, media juga berperan membentuk citra aparat. Polisi, misalnya, bisa digambarkan sebagai pihak represif yang memukul mundur massa, atau sebaliknya, sebagai pengawal demokrasi yang menjaga agar aspirasi tersampaikan tanpa kekerasan.
Melalui teori agenda setting McCombs dan Shaw, kita paham bahwa isu yang dianggap penting oleh media akan dianggap penting pula oleh publik. Jika media menekankan narasi polisi humanis, publik akan lebih percaya bahwa negara hadir menjaga perdamaian, bukan sekadar mengamankan kekuasaan.
Tantangan Independensi Media
Namun, idealisme media tidak selalu berjalan mulus. Tekanan politik, kepentingan ekonomi, dan intervensi pemilik modal sering kali memengaruhi arah pemberitaan. Jika media terlalu dekat dengan penguasa, unjuk rasa bisa distigmatisasi sebagai ancaman. Jika media berpihak pada kelompok tertentu, liputan bisa berubah menjadi alat provokasi.
Inilah tantangan besar dunia pers Indonesia: bagaimana menjaga independensi sekaligus tetap relevan di tengah gempuran media sosial. Tanpa independensi, media kehilangan kepercayaan publik. Tanpa kepercayaan publik, media akan gagal memainkan perannya sebagai salah satu pilar demokrasi.
Indonesia Damai Bukan Tanpa Kritik
Penting untuk ditekankan bahwa Indonesia damai bukan berarti tanpa kritik. Justru, kritik adalah vitamin bagi demokrasi. Kedamaian bukanlah ketiadaan perbedaan, melainkan kemampuan mengelola perbedaan secara bermartabat. Di sinilah peran media sangat strategis: menyalurkan aspirasi dengan cara yang jernih, mengedepankan dialog, dan menghindari framing provokatif.
Jika media konsisten mengedepankan etika jurnalisme yang akurat, seimbang, dan berpihak pada kepentingan publik, maka demokrasi Indonesia akan tumbuh lebih sehat. Rakyat merasa didengar, pemerintah lebih terbuka, dan aparat dipercaya sebagai pengawal aspirasi, bukan alat represi.
Media sebagai Pilar Perdamaian
Indonesia damai adalah cita-cita bersama. Namun cita-cita ini tidak hanya bergantung pada aparat dan peserta aksi, melainkan juga pada media. Dengan memilih narasi yang mencerahkan, menyoroti substansi tuntutan, serta memosisikan diri sebagai jembatan dialog, media dapat bertransformasi menjadi instrumen perdamaian yang nyata.
Demokrasi bukanlah panggung tanpa konflik. Perbedaan akan selalu ada, kritik akan selalu muncul, dan aksi massa akan selalu terjadi. Pertanyaannya: apakah media akan menampilkan perbedaan itu sebagai ancaman, atau sebagai dinamika sehat dalam sebuah bangsa demokratis?
Jawabannya ada di tangan media. Jika media berpihak pada akal sehat, pada kebenaran, dan pada kepentingan publik, maka Indonesia damai bukan sekadar retorika, melainkan kenyataan yang bisa kita wujudkan bersama.