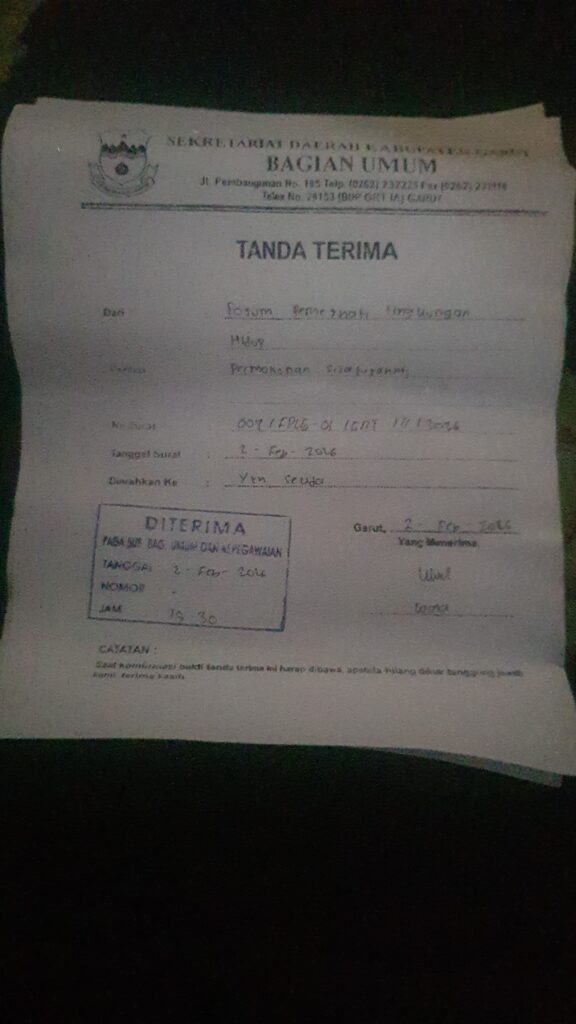![]()
Oleh: Tedi Sutardi
Garut Artikel,Medialibas.com – Negara ini tampak megah di atas lembar konstitusi. Ia berdiri dengan segala simbol kebesaran: istana yang menjulang, gedung parlemen yang kokoh, dan jargon kesejahteraan yang bergaung di setiap pidato pejabatnya. Namun di balik kemegahan itu, tersimpan luka yang dalam luka yang menganga akibat pengkhianatan terhadap nilai-nilai luhur bangsa dan cita-cita kemerdekaan yang dulu diperjuangkan dengan darah dan air mata.
Hari ini, Indonesia bukan sedang miskin sumber daya, melainkan miskin moral kepemimpinan. Di tengah gegap gempita pembangunan dan klaim kemajuan ekonomi, rakyat kecil semakin tertinggal, hukum kehilangan wibawa, dan keadilan sosial menjadi barang langka.
Korupsi Menjadi Sistem, Bukan Lagi Kejadian
Korupsi kini bukan lagi sekadar perbuatan kriminal individu, melainkan penyakit struktural yang mengakar dalam sistem pemerintahan. Di setiap sektor, dari pusat hingga daerah, aroma busuk penyalahgunaan kekuasaan tercium begitu tajam.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 telah tegas menyebutkan bahwa setiap tindakan memperkaya diri sendiri dengan merugikan negara adalah kejahatan luar biasa. Namun, hukum itu sering kali hanya berhenti di atas kertas.
Pejabat yang terbukti menyeleweng masih bisa tersenyum di layar televisi, seolah tak terjadi apa-apa. Ada yang dihukum ringan, bahkan ada yang kembali menduduki jabatan publik setelah bebas.
Sementara rakyat kecil yang mencuri demi bertahan hidup langsung diganjar hukuman berat tanpa belas kasihan. Inilah wajah hukum kita: tumpul ke atas, tajam ke bawah.
Oligarki: Penguasa di Balik Bayang-Bayang Negara
Jika dulu rakyat memimpikan negara yang dikuasai oleh hukum, kini yang terjadi adalah negara yang dikendalikan oleh kekuatan modal. Oligarki politik dan ekonomi telah menjelma menjadi kekuatan tak kasat mata yang menekan, mengatur, bahkan menentukan arah kebijakan nasional.
Privatisasi aset negara, konsesi tambang, penguasaan lahan pertanian dan kehutanan semuanya menjadi bukti bahwa kekayaan alam bangsa telah dikuasai segelintir orang.
Pasal 33 UUD 1945 jelas menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Namun kini, makna “negara” itu direduksi menjadi “pemerintah”, dan pemerintah telah menjadi alat oligarki.
Masyarakat adat terusir dari tanahnya, petani kehilangan sawahnya, nelayan tak lagi berdaulat di lautnya sendiri. Kekayaan bangsa ini mengalir ke rekening para korporat besar yang bersekutu dengan penguasa.
Pajak Naik, Rakyat Makin Terjepit
Ketika defisit anggaran semakin dalam, pemerintah mencari solusi instan dengan menaikkan pajak, menaikkan tarif listrik, BBM, hingga iuran publik lainnya. Ironisnya, yang paling menanggung beban adalah rakyat kecil.
Buruh, pedagang kaki lima, petani, dan pelaku UMKM harus memutar otak untuk bertahan hidup. Sementara para konglomerat justru menikmati insentif fiskal, tax holiday, dan berbagai keringanan lainnya.
Padahal, Pasal 23A UUD 1945 menegaskan bahwa pajak harus diatur secara adil dan proporsional. Tapi faktanya, sistem perpajakan hari ini telah menjadi alat eksploitasi terselubung yang menguras kantong rakyat demi menutupi kebocoran anggaran akibat korupsi.
Dalam logika ekonomi yang sehat, pajak seharusnya menjadi alat pemerataan, bukan penindasan. Namun di negeri ini, logika itu telah dibalik menjadi instrumen penindasan terhadap ekonomi rakyat kecil.
Keadilan yang Mati di Meja Kekuasaan
Di ruang pengadilan, kebenaran seolah kehilangan tempatnya. Hukum yang seharusnya menjadi panglima, kini menjadi pelayan kekuasaan.
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.” Namun dalam praktik, kesetaraan itu hanya menjadi mitos.
Ketika rakyat melawan ketidakadilan, mereka dituduh subversif. Ketika pejabat melanggar hukum, mereka dibela dengan alasan “kekhilafan administratif”.
Inilah wajah suram keadilan kita: hukum digunakan untuk menindas yang lemah, melindungi yang kuat, dan menutup-nutupi kejahatan mereka yang berkuasa.
Ekonomi Tanpa Nurani
Kebijakan ekonomi yang tidak berpihak pada rakyat kecil hanya akan melahirkan kesenjangan sosial yang tajam.
Ketika pajak naik dan daya beli menurun, efeknya sangat nyata:
Konsumsi rumah tangga menurun drastis, padahal menjadi penyumbang utama PDB nasional.
Inflasi meningkat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok.
Daya saing UMKM melemah karena biaya produksi dan distribusi meningkat.
Sementara itu, para pemilik modal besar tetap aman.
Mereka memiliki cadangan kapital dan akses politik yang memungkinkan untuk terus bermain di arena ekonomi nasional.
Akibatnya, jurang antara kaya dan miskin kian lebar, sementara negara terus kehilangan arah moralnya.
Negara yang Kehilangan Jiwa
Sebuah negara tidak akan hancur hanya karena kekurangan uang, tapi karena kehilangan kepercayaan, kehilangan moral, dan kehilangan arah keadilan.
Ketika rakyat tak lagi percaya pada hukum, pemerintah, dan lembaga-lembaga negara, maka sebenarnya negara itu sudah retak dari dalam. Retak moral, retak sosial, retak dalam keadilan.
Hancurnya moral para pejabat adalah awal dari runtuhnya kepercayaan rakyat. Dan ketika kepercayaan itu hilang, negara hanya tinggal menunggu waktu untuk runtuh bukan oleh perang, melainkan oleh pengkhianatan dari dalam dirinya sendiri.
Kembali ke Fitrah Negara
Sudah saatnya bangsa ini kembali menegakkan nilai-nilai dasar konstitusi:
Menempatkan hukum di atas kekuasaan.
Menjadikan keadilan sebagai dasar kebijakan.
Menolak segala bentuk oligarki dan korupsi.
Mengembalikan kedaulatan ekonomi kepada rakyat.
Kita harus kembali ke semangat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan.
Negara harus menjadi pelindung, bukan pemangsa. Negara harus menjadi alat keadilan, bukan mesin penindasan.
Hukum Tanpa Keadilan adalah Kejahatan yang Dilegalkan
Negara di ambang kehancuran bukan karena serangan dari luar, tetapi karena korosi dari dalam: kerakusan, kebohongan, dan ketidakadilan.
Jika sistem terus dibiarkan dikendalikan oleh oligarki dan korupsi dianggap bagian dari budaya birokrasi, maka kehancuran itu bukan lagi ancaman melainkan kenyataan yang sedang berjalan.
“Hukum tanpa keadilan hanyalah topeng dari kejahatan yang disahkan.”