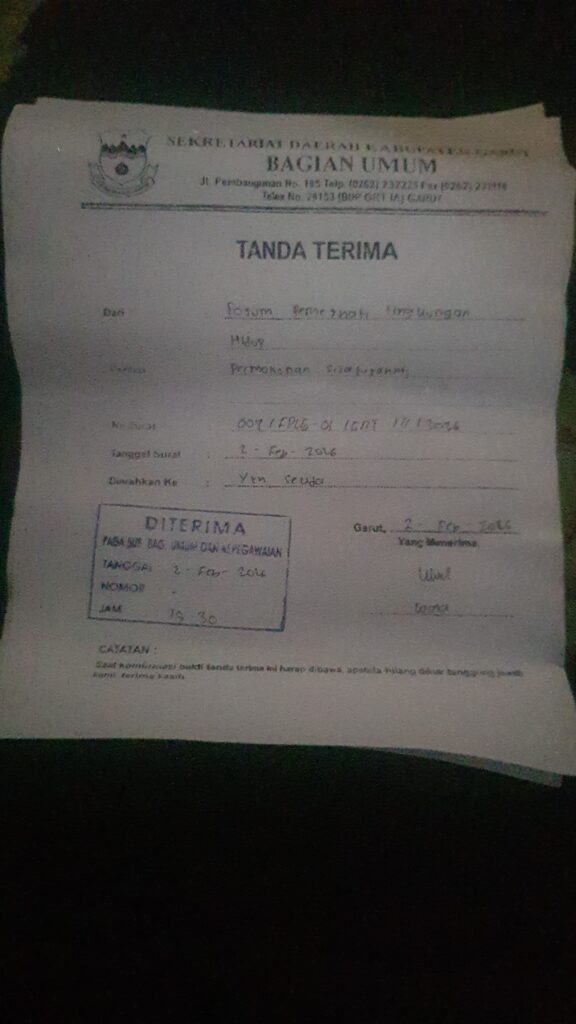![]()
Oleh: Pemimpin redaksi Medialibas.com
Garut Opini – Profesi wartawan selalu menarik untuk dibicarakan. Sejak dulu hingga sekarang, wartawan menempati posisi yang unik: ia ada di tengah pusaran masyarakat, kekuasaan, dan kebenaran. Di satu sisi, wartawan adalah penyampai informasi yang sangat dibutuhkan publik. Namun di sisi lain, wartawan sering kali menjadi sasaran kebencian, intimidasi, bahkan kriminalisasi. Pertanyaan pun muncul, mengapa profesi yang begitu vital dalam kehidupan demokratis justru sering dianggap ancaman?
Wartawan dan Dilema Sosial
Wartawan adalah profesi yang tidak mengenal batas. Mereka bisa berbincang dengan pedagang kecil di pasar pada pagi hari, makan siang bersama pejabat, lalu malam hari bertukar cerita dengan aktivis atau pemuka agama. Wartawan bergerak bebas, lintas kelas sosial, dan menjembatani beragam suara yang sering tak terdengar.
Namun di balik peran vital itu, wartawan justru kerap berhadapan dengan stigma. Sebagian orang menganggap wartawan hanya mencari sensasi. Ada pula yang menuduh wartawan “dibayar” untuk memutarbalikkan fakta. Padahal, di balik sebuah berita, terdapat kerja keras: riset, verifikasi, konfirmasi, hingga uji akurasi yang panjang.
Kenyataan pahitnya: masyarakat mencintai wartawan ketika berita sesuai kepentingannya, tetapi membencinya ketika berita menyentuh sisi gelap yang ingin ditutupi.
Dibutuhkan Kekuasaan,Tapi Juga Dianggap Ancaman
Relasi wartawan dengan kekuasaan ibarat dua sisi mata uang. Kekuasaan membutuhkan wartawan untuk menyampaikan program, citra, dan pencapaian kepada publik. Namun ketika wartawan membongkar kebijakan yang salah arah, korupsi, atau konflik kepentingan, saat itulah wartawan diposisikan sebagai musuh.
Sejarah pers di Indonesia membuktikan hal itu. Pada masa Orde Baru, pers dijinakkan melalui sistem pemberedelan dan sensor. Wartawan yang kritis dianggap subversif. Kini, meski kebebasan pers dijamin UU No. 40 Tahun 1999, praktik pembungkaman tetap terjadi. Bedanya, kini menggunakan pasal-pasal karet: pencemaran nama baik, penyebaran kebencian, atau UU ITE.
Ironis, wartawan yang bekerja untuk kebenaran justru dijerat dengan hukum yang semestinya tidak relevan dengan kerja jurnalistik. Inilah wajah demokrasi yang masih setengah hati.
Risiko Tinggi di Balik Profesi
Menjadi wartawan berarti siap dengan risiko yang tidak kecil. Risiko fisik, psikologis, hingga ancaman terhadap keselamatan diri dan keluarga. Tak jarang, wartawan menjadi korban kekerasan saat meliput aksi demonstrasi, konflik agraria, atau liputan investigasi yang menyentuh kepentingan kelompok kuat.
Kasus wartawan yang dipukul, diintimidasi, atau bahkan dibunuh bukanlah cerita asing. Sayangnya, penyelesaian kasus semacam itu jarang tuntas. Negara seolah tutup mata, dan pelaku kekerasan terhadap wartawan sering lolos dari jerat hukum.
Padahal, jika wartawan bungkam karena takut, maka publik akan kehilangan mata dan telinga. Dan ketika informasi hanya dimonopoli oleh penguasa, demokrasi mati secara perlahan.
Tantangan di Era Digital
Perkembangan teknologi memperparah dilema wartawan. Kini, siapa pun bisa mengklaim dirinya sebagai penyampai berita hanya bermodal gawai dan akun media sosial. Informasi beredar cepat tanpa filter, tanpa verifikasi. Hoaks dan disinformasi menjamur, sering kali lebih cepat dipercaya publik dibanding berita hasil kerja jurnalistik yang panjang.
Akibatnya, posisi wartawan profesional semakin sulit. Di satu sisi mereka dituntut bekerja akurat, berimbang, dan taat kode etik. Di sisi lain, mereka harus bersaing dengan banjir informasi instan yang belum tentu benar.
Fenomena ini justru sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melemahkan kredibilitas pers. Wartawan dilekatkan dengan stigma “pembuat berita palsu”, padahal justru wartawanlah yang berusaha keras memisahkan fakta dari rumor.
Wartawan Sebagai Pilar Demokrasi
Kebebasan pers bukan sekadar hak profesi wartawan, melainkan hak publik untuk tahu. Wartawan bekerja bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan masyarakat luas. Melalui berita, wartawan menghadirkan transparansi, mengontrol kekuasaan, dan membuka ruang diskusi publik.
Sejarah mencatat, kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari peran pers. Para wartawan mengabarkan proklamasi ke seluruh dunia, memastikan bahwa bangsa ini diakui sebagai negara merdeka. Dalam masa reformasi, pers kembali menjadi garda depan untuk membuka tabir kebobrokan rezim.
Sayangnya, di era sekarang, penghargaan terhadap wartawan justru melemah. Pers dianggap sekadar pelengkap, bukan pilar utama demokrasi. Inilah kesalahan besar. Demokrasi tanpa pers adalah demokrasi semu.
Publik Harus Berpihak
Masyarakat pun tidak bisa lepas tangan. Publik sering kali hanya menjadi penonton pasif, bahkan ikut-ikutan menyudutkan wartawan. Padahal, membela wartawan berarti membela hak publik untuk mendapat informasi yang benar.
Jika masyarakat terus membiarkan wartawan diintimidasi, maka pada akhirnya yang dirugikan adalah publik sendiri. Informasi akan dikendalikan oleh mereka yang punya kuasa dan modal, sementara suara rakyat kecil terkubur dalam diam.
Jangan Biarkan Wartawan Sendiri
Wartawan adalah cermin. Mereka memantulkan realitas apa adanya, entah itu menyenangkan atau menyakitkan. Membenci wartawan sama artinya dengan membenci cermin yang memantulkan wajah asli. Jika ada yang tidak suka dengan bayangan di cermin, yang harus dibenahi adalah wajahnya, bukan cerminnya.
Kini, saat banyak wartawan menghadapi kriminalisasi, kekerasan, dan stigma, kita harus bertanya: apakah bangsa ini masih serius menjaga demokrasi? Apakah kita rela kebebasan pers mati perlahan hanya demi kenyamanan segelintir orang yang berkuasa?
Wartawan bukan musuh. Mereka adalah sekutu rakyat. Jika wartawan bungkam, publik akan kehilangan suara. Jika wartawan dibungkam, demokrasi hanya tinggal nama.
Sudah saatnya berhenti membenci wartawan, dan mulai melindungi mereka. Sebab, tanpa wartawan yang bebas, yang tersisa hanyalah propaganda.